Oleh: Humaira Anwar
Aku terbiasa menunggu kedatanganmu di warung kopi, tentu saja. Kau selalu mampir dengan laptopmu di sudut meja sana, memesan kopi hitam gelas kecil, dan duduk sampai berjam-jam. Kadang-kadang kau akan membawa teman-temanmu yang beransel sama besar denganmu, mengedikkan senyum sekilasmu saat melewatiku. Kalian berkumpul dan menceritakan kisah-kisah seru dengan berbagai tanggapan yang tak kalah serunya. Masing-masing akan memesan kopi paling hitam dan santapan porsi paling besar, kemudian menghilang menjelang tengah malam.
Tapi aku lebih sering melihatmu tertegun sendiri di pagi hari pada meja yang sama, memesan kopi pertama di hari itu, dan mencomot beberapa kue selai. Sudahkah kau mengunyah kebahagiaan di hari itu?
Setelah beberapa waktu kau akan menghadapku, memberikan aku senyum letihmu, dan berkata, “berapa?” dengan suara sendu.
Tapi aku lebih senang pada kesempatan yang langka kau akan tersenyum sumringah penuh pengertian dengan kedua sudut bibirmu terangkat indah. Kalimat “berapa?”-mu lebih melegakan daripada minuman-minuman dingin yang kuteguk ketika tiba ke rumah.
Aku terbiasa melihat jalan raya penuh persaingan di pagi dan sore hari. Sesekali di malam hari, jika jam bekerjaku berputar dengan anak bos. Debu dan asap kendaraan mengepul di wajahku saat aku bersedia menambah persaingan itu, mengambil posisi kecil di sisi jalan sebagai pejalan kaki. Jangan ditanyakan betapa ramainya jalanan dengan kendaraan yang lalu-lalang.
Kau tidak perlu cemaskan aku. Aku dapat mempertahankan posisi kecil ini walau terkadang terdesak juga dengan motor-motor beringas yang menjajah trotoar di kala jalan raya tak cukup lebar untuk tubuh mereka. Kau pasti pernah melihat aku-aku yang lain yang terdesak ke sisi rerumputan tangguh di pinggir aspal karena terlalu dijajah oleh pengendara jalanan, bukan? Ah, atau kau mungkin tidak begitu memerhatikan. Kau ‘kan juga salah satu pengendara itu. Harapanku cuma kau masih terlalu baik tidak mengendarai motor besarmu di jelaga untuk pejalan kaki sepertiku.
Aku menempuh 2 km menuju warung kopi itu. Jaraknya tidak seberapa. Aku sudah siapkan minuman cadangan di tas kecil untuk pengisi tenaga di tengah jalan. Aku adalah pejalan kaki penuh strategi, cukup ahli menemukan jalan kecil yang tembus ke tempat-tempat tertentu sehingga dapat memotong jarak agar lebih dekat. Dari strategi inilah aku dapat menemukan kos-kosanmu, yang ternyata berjarak sekian meter dari warung kopi.
Dari strategi inilah aku bertemu dengan banyak orang dengan kisah cinta berbeda di wajahnya. Kau pernah melihat wajah ibu-ibu yang turun dari labi-labi dengan bayi dalam gendongannya, dengan balutan baju berharga tak seberapa, tetapi membawa segunung rasa cinta di wajahnya? Senyumnya syahdu di antara bibir merah berkat lipstik yang dijual murah. Tersenyum malu-malu kepada orang-orang yang ia temui sementara menggendong erat bayinya. Langkahnya gontai menuju pasar kota. Siap membeli kebutuhan dapur keluarga tercintanya.
Atau pernahkah kau menyaksikan wajah-wajah polos penuh kedamaian anak-anak SD yang baru keluar dari sekolahnya? Beramai-ramai berbincang riang sementara menunggu Polantas cantik menggelayut tangan mereka untuk menyeberang jalan. Tas-tas mereka sungguh besar luar biasa jika dibandingkan dengan ukuran tubuh mereka yang masih kecil. Tidak ada kelelahan di wajah mereka jika dibandingkan dengan wajah kakak-kakak mereka yang baru keluar kampus atau perkantoran, orang-orang yang aku temui di sisi jalan raya yang lain.
Tapi kau mungkin tidak pernah tahu. Mungkin kau pernah menyaksikan hal-hal itu di balik laptopmu. Atau di balik layar kaca. Pernahkah kau menyaksikannya secara langsung sehingga kebahagiaan-kebahagiaan kecil di pinggir jalan itu menularimu? Atau pernahkah kau menemukan cinta-cinta terpendam di sudut-sudut hati orang asing dibandingkan dengan cinta-cinta karatan orang di sekelilingmu?
Kurasa kau perlu merasakan hal-hal indah seperti itu. Suatu hari aku pernah melihatmu memarkir motor di depan sebuah pertokoan komputer dengan wajah kusam sore hari. Kau masih menggendong ranselmu yang besar. Sepertinya kau kehabisan suplai cintamu untuk hari itu. Keganasan kantormu pun mungkin satu per satu menyita kebahagiaanmu. Ingin sekali aku membujuk kau untuk menyaksikan tawa seorang tukang parkir di ujung toko dari sela-sela wajahnya yang sawo matang. Sinar matahari yang membara tidak menghanguskan kebahagiaannya.
Saat itu aku tinggal menyeberang jalan untuk menggapaimu dan mengusap wajahmu. Tetapi menyeberang jalan di kota ini pun menjadi PR yang besar bagi pejalan kaki sepertiku. Kau tahu? Aku hampir digilas mobil mengkilap yang mesinnya mungkin rusak di pagi hari itu. Ia mungkin buru-buru ke kantor, tetapi mobilnya kupikir perlu diperbaiki dahulu. Kulihat ia tidak bisa mengendalikan mobilnya karena terus melaju kencang di saat tubuhku masih sekian senti dari mobilnya. Belum lagi kendaraan-kendaraan lain sepertinya ikut-ikutan terlalu lupa untuk memberi peluang kepada orang yang menyeberang.
Aku selalu menanti masa di saat aku dapat menyeberang tanpa ragu untuk mengusap senyummu. Sehingga yang hanya bisa kulakukan saat itu adalah lanjut berjalan dan menolak mengacuhkan siluetmu yang mengecil. Tidak apa-apa, tenang saja. Besok aku akan menemanimu sarapan dengan kopi hitam dan kue selai. Akan kuminta Bang Sen, si peracik kopi itu, untuk menambah tetesan cinta ke dalam ramuan kopi hitamnya. Tidak apa-apa. Ia sendiri sudah berlumuran cinta dari istri dan ketujuh anaknya. Ia pasti tidak keberatan membagi beberapa kepadamu.
Dan, yang aku lakukan adalah menantimu mengedikkan senyum sekilasmu kepadaku. Serta menanti jalan raya reda dari tubuh-tubuh besi bernama kendaraan yang membawa manusia-manusia yang kehabisan cintanya. Agar bisa menyeberang kepadamu.
“Kak, saya pesan kopi di gelas kecil tadi. Berapa?” tanyamu sambil mengeluarkan dompet di depanku.[]



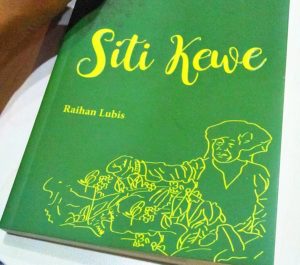


Belum ada komentar