Erwin sedemikian bimbang. Sejak meninggalkan tanah Gayo, dari mengabdikan masa akademisnya sampai bekerja di luar daerah, belum pernah ia berpikir untuk kembali menetap, meski sesekali ia pulang ke kampung halaman untuk mengunjungi keluarganya. Ingatan akan konflik bersenjata yang sempat melanda tanah kelahirannya di tahun 2000-an silam itu, sesekali terngiang.
Beruntung, persahabatan yang langgeng dengan Azmi dan Pri, perlahan memaling perhatiannya kembali ke tanah Gayo. Keadaan traumatis, kepedulian sebagai putra daerah, hingga empati pada muramnya praktik dagang kopi yang membuat petani terperosok di jurang kemiskinan dan lilitan hutang, menyatu dalam benak Erwin.
Baik Pri, Azmi, maupun Erwin sesungguhnya fiksi. Adalah Raihan Lubis, penulis yang mampu mengemas ketiga tokoh ini menjadi poros utama dalam novel perdananya berjudul Siti Kewe. Sabtu (4/11) pekan lalu, penerbit Swarnadipa bekerja sama dengan Deli Art Foundation (DAF) dan Fakultas Kopi Setiabudi menggelar peluncuran novel ini. Kegiatan yang berlangsung di kedai kopi One 4 Co tersebut turut disertai diskusi, menghadirkan antropolog Unimal T Kemal Fasya dan jurnalis senior Iranda Novandi.
Siti Kewe bercerita tentang Erwin, pria Gayo yang merantau lalu menetap di Bali. Beragam pergolakan batin mencuat di tiap sisi cerita, ikut mempengaruhi cara pandang laki-laki itu terhadap tanah kelahirannya sendiri. Kopi menjadi latar utama dari novel ini. “Sepintas novel Siti Kewe kian mewakili kisah hidup saya,” ujar Mahdi, salah seorang peserta diskusi.
Sengaja datang dari Takengon untuk menghadiri peluncuran novel Siti Kewe, Mahdi sempat menceritakan kisah hidupnya sebagai putra asli tanah Gayo. Peristiwa operasi militer di Aceh yang tergambar dalam novel ini, membawa ingatan Mahdi pada pengalaman hidupnya. Dalam diskusi, ia sempat bercerita bahwa konflik bersenjata pada tahun 2000 silam telah merenggut nyawa ayahnya.
“Ayah saya diculik, dan beberapa hari kemudian jenazahnya saya temukan dalam keadaan mengenaskan, masa yang amat mencekam itu terus saya ingat sampai sekarang,” kenangnya.
Kisah nyata yang dialami Mahdi tepat seperti dituliskan Raihan dalam Siti Kewe. Menggunakan sudut pandang orang pertama, di bagian bagian pertama Siti Kewe pembaca akan disajikan cerita tokoh utama Erwin tentang operasi militer di masa-masa reformasi yang akhirnya merembes ke sekitar kampung mereka. Mulanya, Erwin bercerita tentang penculikan dan penembakan yang masih samar-samar, lalu berita lain tersebar bahwa kampung-kampung mulai dijarah dan dibakar. Berita makin terang benderang ketika sekolah dan kantor pemeritahan ikut dibakar oleh OTK, istilah yang amat populer di media massa kala itu untuk menyebut pelaku Orang Tak Dikenal.
Konflik adalah sepenggal cerita yang terungkap dalam novel Siti Kewe. Keadaan serba mencekam kala itu menyebabkan warga lari mengungsi. Namun karena butuh makan, para petani pun bersiasat. Di situlah kaum perempuan mengambil peran penting. Mereka turun mengurusi kebun, menyiangi pohon-pohon, membabat rumput hingga memanen kopi. Dalam tulisannya, dalam novel ini Raihan Lubis juga menyisipkan pujian pada sosok perempuan Gayo.

“Kaum perempuan yang menjadi penyelamat dari kebun-kebun kopi yang terlantar, mereka yang turun ke kebun tak diperlakukan kasar oleh tentara maupun sipil bersenjata,” ujarnya.
Raihan Lubis mengaku plot Siti Kewe adalah potret nyata yang ia dengar dari cerita-cerita warga Gayo. “Bang Mahdi yang tadi sudah berbicara di tengah-tengah kita, beliau narasumber utama dari novel saya. Sebagai seorang Q Grader (sebutan untuk ahli pencicip kopi arabika), bang Mahdi banyak bercerita tentang kopi sebagai wawasan untuk saya. Ia orang yang langsung terlibat mengekplorasi tanaman-tanaman kopi di Gayo,” papar Raihan.
Ia bercerita, inspirasi menulis tentang Gayo muncul saat ia masih berprofesi sebagai jurnalis pada masa konflik sekitar tahun 2000-an. Raihan menemukan banyak kisah yang saat itu tidak bisa ia tuliskan. Walaupun beberapa bagian dalam novel ini merupakan hasil imajinasi, Tapi semuanya berangkat dari kisah nyata.
“Karena banyak penghalang, seperti kondisi keamanan dan kebijakan media tempat kita bekerja juga mempengaruhi itu, cerita-cerita ini lalu mengendap di pikiran, sampai akhirnya ketika saya tidak lagi menjadi jurnalis, saya merasa perlu mengungkapkannya,” ujar Raihan.
Raihan berharap novel Siti Kewe menjadi sebuah preferensi literasi untuk masyarakat gayo. novel ini berangkat dari rasa bangga sekaligus keprihatinan Raihan pada kondisi petani kopi di Gayo. dari hasil wawancara nya terhadap sejumlah anak di sana, banyak dari mereka yang mengekerdilkan pekerjaan tani.
“Anak-anak Gayo itu tidak pernah bangga kalau ayahnya adalah seorang petani kopi. Karena menurut mereka, pekerjaan itu melarat dan banyak hutang. Bahkan ada salah satu pepatah orang Gayo yang mengatakan, ‘cukup lah kami dengan pulpen besar (cangkul), kalian anak-anak kami harus pulpen kecil saja’. Menjadi PNS kah, atau apapun,” jelas Raihan. Dalam lembaran awal novel tersebut ia menuliskan ‘untuk petani kopi Gayo’, sebagai bentuk penghargaan terhadap para petani di sana.
DESKRIPSI GAYO DALAM SITI KEWE
Penggambaran noel Siti Kewe terhadap nuansa kehidupan di dataran tinggi Gayo demikian utuhnya, hingga Iranda Novandi, salah seorang jurnalis yang menjadi pengisi diskusi memuji gaya penulisan Raihan.
“Menariknya, Raihan menyajikan kembali kata-kata lampau bahasa gayo di dalamnya. Saya rasa istilah seperti ‘tetusuk’ itu tidak pernah lagi didengar oleh generasi muda Gayo,” kata Iranda. Dalam novel Siti Kewe, kata ‘Tetusuk’ diartikan sejenis rumput yang dipakai anak-anak Gayo semasa dahulu sebagai odol saat mereka mandi, sedangkan untuk sampo, mereka gunakan perasan jeruk purut.
Iranda juga khawatir tradisi dan tutur bahasa masyarakat Gayo ini tak bertahan lama lagi. Generasi muda Gay mulai meninggalkan bahasa asli mereka, ujarnya.
“Saya sangat apresiatif, terimakasih untuk Raihan. Mengingatkan kami kembali pada bahasa leluhur. Semoga ribuan penutur bahasa Gayo membaca novel ini, dan sudah tergugah hatinya mengajarkan anak-anak yang tidak pandai lagi berbahasa gayo,” harap Iranda.
Cara menterjemahkan percakapan bahasa Gayo juga menjadi catatan Iranda. Dalam novel Siti Kewe, Raihan tidak menterjemahkan secara literer begitu saja. Namun terjemahan itu ia sajikan dalam bentuk penjelasan. “Ini mungkin kehebatan Raihan sebagai salah seorang mantan jurnalis, ia mampu menggubah sebuah percakapan dengan sangat baik,” pujinya.
Antropolog T Kemal Fasya memperhatikan cara Raihan mendeskripsikan nuansa kehidupan masyarakat Gayo. “Dari membaca novel ini, seakan kita ikut merasakan wangi biji kopi dan dinginnya kaki gunung Nur Ni Telong,” ujarnya.
Kisah yang diceritakan dalam Siti Kewe juga tak lepas dari peran kebudayaan Gayo masa lampau. Dialog di dalamnya mampu mengurai lapisan karakter dan ragam perasaan, baik sedih, putus asa, perasaan hampa dan cinta.
“Kisahnya sekompleks dan setua peradaban gayo yang mesolithik,” tambahnya.
MAGISME HINGGA EKSPLOITASI BUDAYA
Siti Kewe bukan lah nama orang. Ia tak lain merupakan sisipan dalam sebuah mantra yang dibacakan sebagian besar petani kopi di Gayo. Di lembaran awal novel ini, Raihan menjelaskan bahwa mantra ini terucap ketika petani melihat bunga-bunga kopi telah keluar.
Terkait sisi magis yang muncul dalam kehidupan masyarakat agraris, sebut antropolog T Kemal Fasya, bukanlah sesuatu yang baru. Kelahiran mantra-mantra dalam sebuah kebudayaan semata harus dimaknai secara simbolis.
“Kita Aceh juga punya tradisi seperti Khanduri Blang, perayaan yang bersifat simbolis, sama halnya tradisi Rabu Abeh, di beberapa wilayah hal ini kadang berbenturan dengan konteks politis, sehingga dianggap bid’ah dan segala macam, padahal ini punya makna yang lebih besar dari apa yang terlihat di permukaan,” terang Kemal.
Di sisi lain, menurutnya kemunculan kopi Gayo sebagai ‘primadona’ di kancah luar, juga menyemat ancaman, seperti perubahan iklim dan menurunnya aspek religio-magis pada masyarakat umum terhadap kopi Gayo.
“Perubahan iklim membuat ladang kopi makain banyak diserang hama. Dan itu nantinya juga berpengaruh pada kualitas kopi. Hal lain menurut saya, sisi aspek religio-magis yang ada di tanaman kopi Gayo sudah tergerus,” tambahnya. Gempuran modernitas, yang berkelindan dengan pandangan ekonomi yang instan dan kapitalis turut mengubah fungsi kopi itu sendiri.
Kemal menyebutkan telah terjadi semacam komodifikasi budaya, yakni perubahan dari sebuah produk yang semula bukan bersifat komersial menjadi komoditas. Kopi Gayo sendiri, lebih menjelma sebagai objek komersial, sedang peran esensinya sebagai bagian dari budaya perlahan pudar
“Suatu saat, kita mungkin kehilangan ritual-ritual seperti Siti Kewe ini, padahal inilah makna esensial dari kopi Gayo, sebuah berkah yang tumbuh dari tanah yang ‘dituahkan’, ia menghidupi masyarakat Gayo dan berdampingan dengan segala pergolakan yang terjadi di sepanjang masyarakat itu hidup,” imbuh Kemal.
KOPI, KOMODITAS PERDAMAIAN
Etnis Gayo memiliki sumber referensi ke dua terbanyak setelah Aceh. Snouck Hurgronje pada tahun 1906 menulis buku The Acehnese, yang didalamnya terdapat beberapa keterangan tentang karakter masyarakat etnis ini. Beberapa hasil penetlitian para sejarawan, terungkap masyarakat Gayo memiliki karakter setia, rasa solidaritas yang tinggi.
“Kebiasaan etnografi semacam ini biasanya dimiliki oleh masyarakat yang ada di pulau-pulau kecil,” kata Kemal.
Hal ini tentu berbeda dengan masyarakat di wilayah lainnya, yang rasa saling curiganya makin besar akibat konflik yang berkepanjangan. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, Gayo dikenal tidak memiliki kesadaran traumatis.
“Ada banyak modal sosial di masyarakat Gayo. Problemnya adalah bagaimana kita memetakan lagi potensi multikultural di antara masyarakat Aceh ini dalam ruang yang lebih sehat. Pertemuan yang lebih memperkaya korelasi sosio-kutural kita,” sebutnya. Masyarakat kerap terpecah karena pandangan politik, “Namun kopi yang mempersatukan kita,” tegas Kemal disambut tepuk tangan para peserta diskusi.
Tak jarang, kopi Gayo disebut sebagai ikon perdamaian. Jurnalis Iranda Novandi menanggapi, dalam setiap permasalahan yang muncul baik dari rumah tangga hingga masyarakat di Gayo, semua didamaikan dengan duduk meminum kopi.
“Dapat cair begitu saja setelah duduk meminum kopi. Dan itu saya kira itu yang disebut demokrasi kopi,” kata pria asal Gayo ini.[]
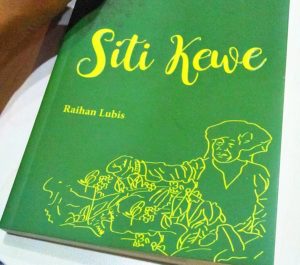






Belum ada komentar